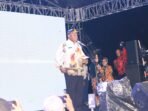Oleh: Elkami dan Hubdo
Sebuah surat putih datang bersama seruan ombak Pasifik. Ia meniti riak, meluncur menembus senja, lalu berlabuh di hati seorang anak manusia. Surat itu dibawa oleh KM G Dempo, sebuah pamitan terakhir dari cinta abadi bernama Elkami. Cinta itu awalnya indah, namun akhirnya berujung pilu, menggores jiwa yang rapuh. Saat itulah Elkami sadar, bahwa senja hanya sejenak: berpendar indah, lalu padam, ditelan gelap bumi.
Elkami dan Hubdo, dua bersaudara tunggal, hidup dalam kesederhanaan sebuah rumah kayu di pesisir Pasir Putih, perbatasan Dogi dan Nabire. Kehidupan mereka tak berlimpah harta, tapi bahagia. Dunia bagi mereka sesederhana awan putih yang saban pagi mengelilingi puncak Gebay, jernih, tenang, penuh janji. Relasi mereka adalah cinta yang tak kasatmata: mengalir dalam senyap, namun hangat seperti pelukan cahaya matahari pertama.
Waktu lalu menyapa dengan perpisahan. Elkami harus merantau ke Jayapura untuk menempuh SMA, sementara Hubdo, masih kecil, belajar di SD Mandala Nabire. Tahun-tahun berjalan. Elkami duduk di kelas dua belas, Hubdo naik ke kelas enam. Jarak kota dan lautan memisahkan raga, tapi kasih mereka tak pernah pupus.
Desember 2024, Elkami pulang kampung. Mereka kembali bersua, merayakan Natal sederhana bersama kedua orang tua. Namun kebahagiaan itu tak utuh. Hubdo mulai sering batuk, dadanya sesak. Tubuhnya ringkih, matanya redup, seperti lilin yang sekarat. Elkami cemas, hatinya resah, tapi ujian akhir menunggu. Ia terpaksa kembali ke Jayapura.
Di Nabire, sebelum berangkat, ia sempat menjenguk adiknya di RSUD Siriwini. Hubdo terbujur lemah. Elkami mencoba tersenyum di hadapan adiknya, meski hatinya hancur berderai di dalam.
Malam itu, hujan mengguyur pelabuhan Samabusa. Gelap, dingin, penuh air mata. Elkami naik ke KM G Dempo, meninggalkan Nabire dengan hati patah. Di geladak kapal, ia berbaring, berusaha tidur, namun hatinya resah. Tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari kakaknya:
“Elkami, adik kandungmu, Hubdo… sudah meninggal dunia.”
Dunia runtuh. Elkami membeku, lalu melempar ponselnya hingga pecah menabrak dinding kapal. Laut Pasifik jadi saksi air matanya yang pecah berderai. Dalam hati ia meraung:
“Hidup ini apa? Kau rampas satu-satunya harta dalam hidupku. Wahai dunia, kau kejam! Seandainya kapal ini tenggelam malam ini, biarlah aku ikut adikku… biarlah aku terbenam bersama cintaku yang paling murni.”
Namun kapal itu terus berlayar. Ombak tetap mendesir, mesin tetap berdengung. Ada ratusan jiwa lain di atas kapal, ia hanya bisa pasrah, menatap kegelapan Pasifik yang luas, sambil merelakan separuh dirinya hilang di malam yang panjang.
Keesokan harinya, KM G Dempo tiba di Jayapura. Dengan uang pas-pasan dari orang tua, Elkami berusaha mencari tiket pesawat pulang. Berkat uluran sahabatnya, Paul, ia berhasil kembali.
Di Nabire, Paul menjemputnya. Mereka berdua menembus jalan pedalaman dengan motor, melewati hutan, sungai, dan bukit yang sunyi. Tiga jam perjalanan terasa seperti seribu tahun, sebab hatinya hanya ingin sampai.
Sesampainya di rumah, Elkami berlari ke jenazah adiknya. Ia rebah di samping tubuh Hubdo yang kaku dan dingin. Tangisnya pecah. Dengan suara bergetar ia berbisik:
“Adik… maafkan kakakmu. Kakak gagal menjagamu. Kakak pergi menuntut ilmu, tapi meninggalkanmu sendirian di batas nyawa…”
Langit sore itu mendung. Seakan bumi pun berduka bersama Elkami.
Bagi Elkami, sejak malam itu laut Pasifik dan KM G Dempo menjadi luka abadi. Hidupnya kini seperti bulan tanpa bintang, redup dan sepi. Namun jauh di lubuk hati, ia percaya: persaudaraan mereka yang terputus di bumi telah bersambung di langit. Hubdo kini beristirahat di pelukan cahaya Tuhan, sementara Elkami melanjutkan hidup, membawa cinta itu sebagai kompas dalam gelapnya dunia.
Hidup adalah perjalanan singkat, dan yang abadi hanyalah kasih yang tulus. Dari luka yang paling dalam, Elkami menemukan cahaya, bahwa doa adalah sayap yang membuat cinta tetap terbang melampaui batas ruang dan waktu.
Bagi siapa pun yang pernah kehilangan, kisah ini berbisik lembut: jangan takut. Karena di setiap hati yang mencinta, selalu ada jembatan antara bumi dan surga.
Setiap jiwa adalah kitab terbuka, ditulis oleh waktu dengan tinta kebahagiaan dan air mata. Ada kisah yang lahir dari tawa, ada pula yang tumbuh dari kehilangan. Cerita ini adalah nyanyian sunyi tentang dua saudara dari Nabire, Elkami dan Hubdo, sebuah kisah cinta persaudaraan yang menembus batas usia, jarak, bahkan kematian.
Elkami selalu percaya bahwa hidup adalah anugerah yang harus dirawat, sementara Hubdo, adiknya, melihat hidup sebagai perjalanan singkat yang harus dijalani dengan berani. Dua pandangan yang berbeda, tetapi justru menyatukan keduanya dalam ikatan kasih yang tak tergoyahkan.
Namun takdir kerap datang tanpa mengetuk. Hari itu, Hubdo dipanggil Sang Khalik, meninggalkan Elkami dengan dada yang patah. Hujan Nabire turun deras seolah ikut meratapi perpisahan itu. Di tengah keheningan duka, Elkami sadar bahwa air matanya tidak bisa memanggil kembali yang telah pergi.
Sejak saat itu, ia menyalakan lilin doa setiap malam. Ia percaya, cahaya kecil itu mampu menembus gelap, menyeberangi langit, hingga sampai ke hadapan Hubdo di negeri cahaya. “Engkau tidak pergi,” bisiknya lirih, “engkau hanya pulang lebih dahulu.”
Waktu bergulir, luka perlahan menjelma menjadi kekuatan. Elkami belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan undangan untuk memahami makna terdalam dari kasih. Di setiap senja Nabire, ia memandang laut, meyakini bahwa di balik cakrawala, adiknya tersenyum damai.
Kasih persaudaraan itulah jembatan abadi: menghubungkan bumi dan surga, mengikat yang hidup dengan yang telah berpulang. Tidak ada maut yang mampu meruntuhkannya, karena cinta sejati selalu menemukan jalannya.
Hidup adalah perjalanan singkat, dan yang abadi hanyalah kasih yang tulus. Dari luka yang paling dalam, Elkami menemukan cahaya, bahwa doa adalah sayap yang membuat cinta tetap terbang melampaui batas ruang dan waktu. Bagi siapa pun yang pernah kehilangan, kisah ini berbisik lembut: jangan takut. Karena di setiap hati yang mencinta, selalu ada jembatan antara bumi dan surga. [*]
)* Penulis adalah Michael Dogomo, yang melukiskan kisah semasa hidupnya bersama sang adik, Hubdo, sebagai jembatan abadi antara kenangan dan doa.