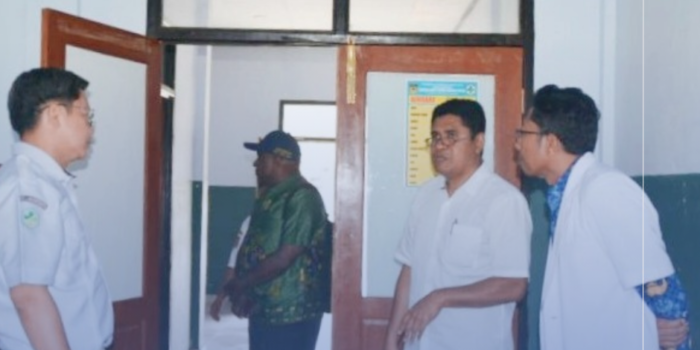Oleh: Yeremias Edowai
Pada tahun 1938, tim Hindia Belanda cikal bakal Timnas Indonesia menorehkan sejarah sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia Prancis. Di antara sebelas pemainnya, berdiri berdampingan pemain pribumi, keturunan Belanda, dan Tionghoa dalam satu kesebelasan. Mereka kalah telak 0–6 dari Hungaria, tetapi sejarah mencatat keberanian mereka sebagai tonggak eksistensi bangsa di panggung dunia.
Zaman itu belum mengenal media sosial. Tak ada kolom komentar, tak ada akun anonim yang menghina. Namun ada sesuatu yang lebih luhur dari sekadar skor: kehormatan untuk bermain tanpa hinaan identitas, tanpa cibiran warna kulit, tanpa diskriminasi asal daerah. Mereka bermain demi lambang di dada, bukan demi validasi digital.
Delapan puluh tujuh tahun berselang, lambang Garuda masih sama, tetapi atmosfer pendukungnya telah berubah. Di era digital, suporter bukan lagi sekadar mereka yang bersorak di tribun stadion, melainkan mereka yang menulis di layar ponsel. Dan di ruang maya itulah muncul luka sosial baru bagi sepak bola kita: rasisme terhadap pemain sendiri.
Ketika Dukungan Berubah Menjadi Luka
Nama-nama dari Timur, Todd Rivaldo Ferre, Boaz Solossa, Yanto Basna, Ricky Kambuaya, hingga Yakob Sayuri menjadi kebanggaan nasional. Mereka membawa semangat dan darah baru bagi Timnas Indonesia. Namun, setiap kali performa mereka menurun, linimasa media sosial berubah menjadi arena penghinaan rasial.
Puncaknya terjadi pada 2025, usai laga Indonesia kontra Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakob Sayuri menjadi korban serangan brutal di Instagram. Kolom komentarnya dipenuhi kata-kata seperti: “Gara-gara monyet ini Indonesia kalah.” “Hitam, kampungan, main di tarkam aja.” “Papua lambat, kasar, ga guna.”
Komentar-komentar itu bukan sekadar emosi sesaat, melainkan ekspresi dari prasangka sosial yang telah mengendap lama dalam kesadaran kolektif bangsa. Ironinya, hinaan itu datang dari mereka yang mengaku “pencinta Timnas”. Inilah paradoks besar sepak bola kita: kita ingin Garuda terbang tinggi, tapi kita sendiri mematahkan sayapnya.
Rangkaian Kasus dan Pola Kekerasan Digital
Sejak 2019 hingga 2025, daftar panjang kasus rasisme terhadap pemain Papua terus menodai wajah sepak bola nasional. Pada Mei 2025, Yakob dan Yance Sayuri menjadi korban ujaran rasis usai laga Malut United kontra Persib Bandung. Mereka akhirnya melapor ke Polda Maluku Utara. PSSI dan PT LIB mengecam keras, tetapi kasusnya berakhir tanpa kejelasan hukum.
Patrich Wanggai juga pernah menjadi sasaran hinaan serupa di Piala Menpora 2021. Komentar seperti “monyet” dan “hitam goblok” membanjiri akunnya. Meskipun publik mengecam, pelaku tak pernah diidentifikasi.
Kasus lain menimpa pelatih Ardiles Rumbiak dan pemain Rivaldo Wally dari Belitong FC (2022), serta pemain belakang Persebaya (2023) yang juga diserang di media sosial. Bahkan legenda seperti Boaz Solossa berkali-kali dihina karena ekspresi emosionalnya di lapangan, memicu lahirnya kampanye “Respect for Papua” di kalangan suporter.
Bahkan pada level klub, tim Persipegaf Pegunungan Arfak, Papua Barat, menjadi korban umpatan rasis di kompetisi Liga 4 musim 2024/2025. Rangkaian peristiwa ini menegaskan: meskipun kecaman sering terdengar dari institusi sepak bola, rasisme terhadap pemain Papua masih hidup dan brutal di ruang digital. Ia mencerminkan kegagalan kolektif bangsa dalam menegakkan kemanusiaan dan sportivitas sejati.
Rasisme: Luka yang Tak Terlihat
Ketika seseorang menulis “Papua monyet, otak kosong, hitam pekat,” ia bukan sedang menilai strategi permainan. Ia sedang menelanjangi cara berpikir bangsa yang gagal memahami arti keberagaman. Rasisme di ruang digital adalah bentuk kekerasan modern: tidak meninggalkan lebam di wajah, tetapi meninggalkan luka di jiwa.
Dalam psikologi olahraga, penghinaan berbasis identitas berdampak langsung pada keseimbangan emosi, konsentrasi, dan motivasi atlet. Setiap ejekan menimbulkan (fear of failure) rasa takut gagal karena takut dihina. Penelitian Lee & Jang (2023) membuktikan bahwa ujaran kebencian online meningkatkan stres, kelelahan mental, dan burnout pada atlet muda Asia Timur. Fenomena yang sama kini terjadi di Indonesia.
Bagaimana mungkin pemain bisa tampil maksimal jika setiap kesalahan kecil berisiko memicu gelombang kebencian nasional?
Fanatisme Tanpa Empati
Netizen Indonesia kerap membanggakan diri sebagai “suporter paling fanatik di Asia Tenggara.” Namun fanatisme tanpa empati hanyalah anarkisme digital.Media sosial kini berubah menjadi tribun gelap tanpa etika. Orang bebas menghina seolah pemain adalah robot tanpa perasaan. Padahal di balik seragam merah putih, ada manusia dengan keluarga, air mata, dan kebanggaan yang sama.
Ketika seorang pemain Papua membaca komentar seperti, “Orang Papua cuma kuat lari, otaknya nggak jalan,” ia tidak hanya merasa terluka, tapi juga terasing di negaranya sendiri. Inilah puncak dari nasionalisme semu: mencintai Garuda, tapi menolak warna bulunya yang berbeda.
Persipura dan Nasionalisme dari Timur
Untuk memahami luka hari ini, kita perlu menoleh ke sejarah panjang Persipura Jayapura. Sejak 1960-an, Persipura bukan sekadar klub sepak bola, melainkan simbol martabat dan kesetaraan orang Papua. Dari stadion Mandala lahirlah nama-nama besar: Boaz dan Ortizan Solossa, Lukas Rumkabu, Imanuel Wanggai, hingga generasi Sayuri.
Bagi orang Papua, sepak bola adalah bahasa persaudaraan. Ia menyatukan perbedaan suku, bahasa, dan gereja. Sepak bola menjadi alat pembebasan simbolik dari stereotip lama: bahwa Papua tertinggal, kasar, dan tak disiplin.
Namun ketika mereka bermain di luar tanahnya, mereka membawa dua beban: harapan untuk membanggakan, dan risiko dihina karena asal-usul. Tanpa Timur, sejarah sepak bola Indonesia tak akan pernah lengkap. Tetapi penghormatan sosial terhadap pemain Papua belum pernah setara dengan kontribusi mereka.
Akar Sosial dan Warisan Kolonial
Rasisme di sepak bola Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari akar sosial yang panjang: warisan kolonialisme dan sistem sosial yang timpang. Pada masa kolonial, warna kulit dan asal daerah menjadi penanda status. Pola pikir itu bertahan: yang terang dianggap “maju”, yang gelap dianggap “terbelakang”.
Stereotip ini merembes ke dunia olahraga. Pemain Papua sering dilabeli “fisik kuat tapi taktik lemah” hingga sebuah asumsi yang bukan fakta biologis, melainkan bias sosial yang diwariskan turun-temurun.
Media, pendidikan, bahkan humor publik sering memperkuat bias ini. Mereka lebih sering menyoroti emosi dan “kekuatan fisik” pemain Papua ketimbang kecerdasan taktis dan strategi mereka. Inilah bentuk diskriminasi halus (microaggression) yang menormalisasi rasisme struktural dalam olahraga.
Dunia Bergerak, Indonesia Terlambat
Rasisme terhadap atlet bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Eropa, Marcus Rashford, Vinícius Júnior, dan Romelu Lukaku pun pernah menjadi sasaran. Namun di sana, hukum bergerak cepat. Polisi menahan pelaku, klub didenda, dan kampanye Zero Tolerance dijalankan secara ketat.
Indonesia punya spanduk “Say No to Racism,” tapi hanya sebagai ornamen formal. Tidak ada sanksi tegas, tidak ada edukasi digital, tidak ada perlindungan psikologis. Kita bangsa yang lebih pandai mengecam daripada memperbaiki. Perbedaan itulah yang membuat luka di sini bertahan lebih lama.
Luka Psikologis dan Lingkaran Kekalahan
Dalam teori psychological well-being (Ryff, 1989; Deci & Ryan, 2020), kesejahteraan mental adalah fondasi performa atlet. Namun, ketika ujaran kebencian menghujani mereka, semangat runtuh satu per satu: kehilangan otonomi, percaya diri, dan rasa diterima. Bayangkan Yakob Sayuri, baru keluar dari ruang ganti usai kekalahan, membuka ponsel, lalu membaca ribuan komentar yang menghina warna kulitnya.
Bagaimana mungkin ia bisa fokus untuk laga berikutnya? Rasisme tidak hanya melukai moral, tetapi juga menghancurkan performa. Dan ketika performa menurun, publik kembali menghujat. Begitulah lingkaran setan yang mematikan regenerasi atlet dari Timur.
Kelemahan Institusi dan Butanya Suporter
PSSI, LIB, dan APPI berkali-kali menyerukan “No Racism”. Namun implementasinya berhenti di kata-kata. UEFA punya sistem Zero Tolerance, sementara di Indonesia, pelaku cukup minta maaf di kolom komentar, lalu dilupakan.
Federasi sepak bola Indonesia harus bertindak konkret dengan membangun sistem pelaporan ujaran kebencian digital yang efektif, menjalin koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan kepolisian untuk menindak pelaku rasisme daring, serta memberlakukan sanksi tegas berupa larangan masuk stadion bagi suporter yang terbukti melakukan diskriminasi.
Selain itu, federasi perlu menyediakan layanan konseling psikologis bagi pemain korban rasisme dan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pembinaan suporter muda. Tanpa langkah-langkah nyata tersebut, bangsa ini hanya akan terus menumpuk slogan di atas luka yang tak pernah sembuh.
Literasi Digital dan Tanggung Jawab Moral
Indonesia memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet (APJII, 2024), tetapi hanya 30% yang memahami hukum ujaran kebencian. Mayoritas pengguna masih menganggap hinaan rasis sebagai “bahan bercanda.”Padahal Nielsen Sports (2022) mencatat, perilaku rasis dapat menurunkan nilai komersial liga hingga 40%. Artinya, rasisme bukan hanya dosa moral, tetapi juga bunuh diri ekonomi.
Kampanye melawan rasisme harus dimulai dari akar, dengan menghadirkan pesan anti-rasisme di setiap pertandingan sebagai bentuk pendidikan publik yang konsisten. Upaya ini perlu diperkuat melalui kolaborasi antara media, klub, dan para influencer untuk membangun literasi digital yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab dalam berkomentar di ruang daring.
Di sisi lain, penegakan hukum yang nyata terhadap pelaku ujaran kebencian daring menjadi langkah penting agar keadilan tidak berhenti di wacana. Sebab, rasisme tidak akan hilang hanya dengan kecaman, melainkan melalui pendidikan dan keberanian untuk berubah.
Papua dan Makna Kemanusiaan
Papua tidak hanya memberi pemain, tetapi juga memberi nilai hidup: “Kitorang basudara.” Artinya: kita semua bersaudara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jika semangat ini dihidupkan di seluruh stadion dan linimasa digital Indonesia, sepak bola akan kembali menjadi rumah persaudaraan, bukan arena penghinaan.
Ketika seorang pemain Papua mengenakan lambang Garuda di dada, ia membawa tanah, laut, dan gunungnya bersama harapan bangsanya. Setiap hinaan terhadap mereka bukan hanya melukai individu, melainkan menampar nurani bangsa.
Penutup: Garuda yang Terluka
Rasisme terhadap pemain Papua adalah luka moral bangsa yang terus menganga di tengah sorak-sorai stadion dan riuh kolom komentar media sosial. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi kebangsaan ketika keberagaman hanya dipuji dalam pidato, tetapi gagal diwujudkan dalam sikap.
Di lapangan hijau, para pemain Papua telah memberikan segalanya hingga keringat, bakat, dan kebanggaan. Namun yang mereka terima sering kali adalah cemooh, ejekan, bahkan serangan yang mengikis rasa kemanusiaan. Luka itu bukan hanya milik mereka, tetapi milik kita semua yang membiarkan suara kebencian terus bergema tanpa perlawanan.
Lebih dari sekadar olahraga, sepak bola adalah cermin wajah bangsa. Jika di sana masih hidup diskriminasi, maka yang tercermin bukan semangat persatuan, melainkan perpecahan yang disulut oleh prasangka.
Pemerintah, federasi, dan masyarakat harus memahami bahwa setiap ejekan berbau rasis tidak hanya melukai pemain, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia. Sebab bangsa yang tak mampu menghormati anak-anaknya sendiri akan kesulitan dihormati bangsa lain.
Garuda tidak akan benar-benar terbang tinggi jika sayap Timurnya terus dipatahkan oleh ejekan dan kebencian. Pemain Papua bukan hanya bagian dari tim nasional, tetapi bagian dari jiwa Indonesia itu sendiri. Dalam sepak bola, sebagaimana dalam hidup, kemenangan sejati bukanlah soal skor di papan, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan manusia di lapangan sampai dengan hormat, setara, dan penuh cinta pada kemanusiaan.
Kini saatnya bangsa ini menatap cermin dan bertanya dengan jujur: apa arti kebanggaan jika diraih di atas penderitaan sesama anak bangsa? Nasionalisme tidak seharusnya lahir dari tepuk tangan yang menutup telinga terhadap jeritan ketidakadilan.
Indonesia harus belajar bahwa rasisme tidak bisa dilawan dengan diam atau slogan kosong, melainkan dengan kesadaran kolektif untuk berubah dari ruang ganti pemain hingga ruang kelas, dari tribun stadion hingga ruang digital. Perubahan itu menuntut keberanian moral, empati sosial, dan komitmen politik yang nyata untuk menciptakan ruang sepak bola yang adil, aman, dan manusiawi bagi semua anak bangsa.
Hanya ketika keberagaman diterima sebagai kekuatan, bukan ancaman, Indonesia akan menemukan kembali makna sejati dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda tidak akan benar-benar terbang tinggi jika salah satu sayapnya terus dilemahkan oleh prasangka dan diskriminasi. Ia hanya akan menjadi simbol kosong tanpa jiwa.
Maka, saat kita bersorak menyebut nama Garuda di setiap pertandingan, seharusnya kita juga mengingat satu hal: bahwa kemerdekaan dan kebanggaan sejati baru lahir ketika setiap anak bangsa termasuk mereka yang datang dari Timur, dihormati sebagai bagian utuh dari Indonesia. [*].
)* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua.